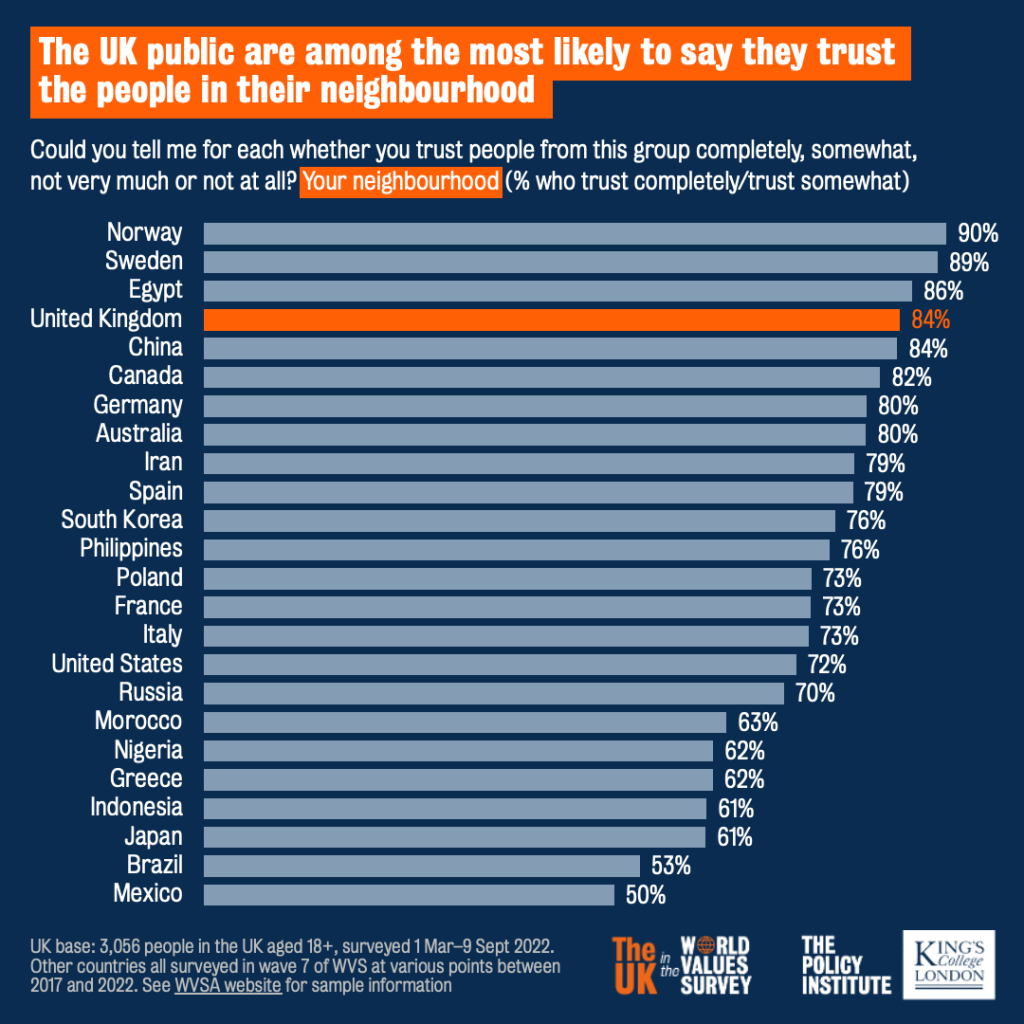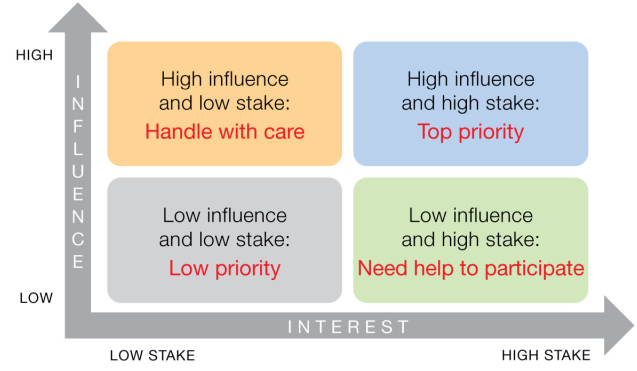Sori kalo judulnya provokatif. Tapi kenyataannya, gw pun baca buku ini karena jadi “korban provokasi” obrolan kaum urban. Bahkan dalam berbagai situasi percakapan, buku ini sering disebut. Lantas apa yang membuatnya spesial? berbicara tentang filosofi stoikisme, ini jelas bukan buku dasarnya, bukan juga buku pertama dalam bahasa Indonesia. Tapi saat gw baca buku ini, dia udah jadi mega best seller, dimana yang gw pegang sendiri udah cetakan ke-25. Uwow.
Begitu gw baca bagian pengantar, jujur, hook-nya menurut gw dapet banget. Om Piring (panggilan dari Henry Manampiring, sang penulisnya) langsung cerita “Saya menderita major depressive disorder’ atau simpelnya “saya didiagnosa depresi (oleh psikiater)”. So, buku ini bukan cuma tentang apa itu stoikisme, tapi lebih ke stoikisme dan relevansinya dengan kehidupan dia pribadi. Itu menurut gw cerdas dan jadi terasa tulus kenapa dia akhirnya nulis buku ini. Gw malah jadi belajar cara menulis buku dari sini. Kalo cuma ngomongin “stoikisme adalah.. bla bla bla”, om Piring bakal kalah dengan para pakar filosofi, karena dia sendiri bukan doktor di bidang itu. Text book tentang stoikisme pun sudah relatif banyak. Untuk orang-orang yang betul tertarik, akan mikir “ngapain gw baca buku ini? mending baca tulisan para filsuf Romawi atau Yunani langsung aja”. Untuk nulis buku teori, penulis harus saling adu kredibilitas. Tapi untuk nulis pengalaman pribadi, gak ada yang lebih kredibel dibanding orang itu sendiri. So, memadukan “text book” tentang prinsip-prinsip dasar stoikisme dengan perjalanan hidup adalah formula yang menarik, dan akhirnya gw jadi nerusin baca buku ini, alih-alih karena ingin jadi ahli Stoa, gw lebih pengen tahu gimana si Stoikisme merubah hidup dia.
Secara umum, efek dari buku ini ke pembaca akan tergantung dari latar belakang pembaca tersebut. Gw ngebanyangin, kalo gw belum pernah denger apa itu stoikisme sebelumnya, kayaknya impresi gw akan ngerasa buku ini sangat breakthrough dan life-changing. Tapi karena gw udah agak familiar dengan stoikisme dan konsepnya tentang berfokus pada yang bisa kita kontrol (atau yang di buku ini disebut ‘dikotomi kendali’), efeknya jadi gak terlalu se-wah itu. Tapi kalo dari tulisannya sih, kayaknya om Piring termasuk kategori orang yang pertama. Doi nulis ini di 2018 setelah nemu buku wajib filsuf Stoa di toko buku, artinya ini konsep yang baru dia temukan saat itu, dan jadinya terasa mencerahkan, sehingga dirasa harus dibagikan ulang. Tapi walau demikian, gw tetep belajar banyak kok dari buku ini.
Kelebihan buku ini adalah dia memberi contoh penerapan prinsip-prinsip Stoa dalam kehidupan sehari-hari, misal: dalam menghadapi hal (yang dianggap) buruk yang simpel seperti macet, haters, jatuh, ditolak, sampai menghadapi hal gelap seperti kematian. Ini menegaskan bahwa Stoikisme relevan di semua lini, tanpa pandang bulu, dan bahkan sampai sekarang, setelah lebih dari 2000 tahun konsep ini diperkenalkan.
Untuk melengkapi catatan pengalaman, om Piring juga bawa pasukannya dari berbagai latar belakang, ada yang psikiater psikosomatis, psikolog, (self-claim) Stoa, dan (non self-claim) praktisi Stoa. Ini memperkaya bukunya dengan berbagai perspektif lain, yang menurut gw efektif.
Ngomong-ngomong, alasan judul buku Filosofi Teras dipilih, ternyata ya memang literal, karena filosofi Stoa diajarkan di teras XD
Di luar dikotomi kendali, tetep banyak yang gw pelajari dari sini, karena om Piring menjelaskannya dengan lebih dalam. Beberapa poin yang gw highlight:
- Konsep yang paling menarik perhatian gw: practice poverty. Katanya Stoa menganjurkan kita untuk latihan menderita secara rutin. Kenapa? Karena kesenangan apapun (kekayaan, ketenaran, makanan, sex, dll) jika dialami terus menerus, dia akan menjadi norma dan rasanya jadi biasa saja. Jadi para Stoa menganjurkan kita untuk sering-sering “turun level”. Misal: biasa makan enak, cobalah 4 hari seminggu makan makanan murah dan standar. Atau kalau biasa kemana-mana naik mobil, cobalah lebih rutin naik motor. Tujuannya, untuk merasakan kembali nikmat atas apa yang telah kita miliki, yang berdampak kita bisa lebih bahagia.
- Emosi adalah bagian dari rasio yang membentuk opini. Saat kita merasakan emosi negatif, itu karena opini kita menyatakan bahwa sesuatu itu buruk. Begitupun sebaliknya. Saat merasakan emosi positif, itu karena opini kita menyatakan bahwa sesuatu itu baik, Para Stoa akan melihat segala sesuatu sebagai netral, tidak baik dan tidak buruk. Ini akan ngasih diri kita kunci untuk mengendalikan emosi tersebut.
- Jika opini berkaitan dengan masa kini, yang muncul adalah rasa senang atau rasa sesal. Tapi jika berkaitan dengan masa depan, maka yang keluar adalah perasaan iri atau takut. Walau yang ditakutkan tidak kejadian, merasa takut saja sebenarnya sudah ada “ongkosnya” (cost of worry), yaitu: energi pikiran, waktu dan uang, juga kesehatan tubuh.
- Aplikasikan STAR; Stop – Think – Assess – Respond. Intinya, saat terjadi sesuatu, jangan dulu bereaksi. Stop dulu, pikirkan, pisahkan sesuatu itu dengan opini atau persepsi kita, baru ambil pilihan terbaiknya yang bijaksana.
- Di buku sempat disinggung juga tentang CBT atau Cognitive Behavioral Threapy, dimana dinyatakan oleh pakarnya bahwa CBT mendukung filosofi Stoa, karena kognitif berpengaruh pada perilaku, begitupun sebaliknya, perilaku bisa mengubah pikiran. Untuk yang kepo tentang CBT, bisa nonton video Youtube aku berikut ini: (hehe, malah promo)
So, kembali ke pertanyaan di judul, apakah buku ini worth the hype? Karena isinya positif, gw sih bilang worth it 😀
Filsafat masih sering terasa jauh dari kalangan umum, dan buku ini bisa jadi pengantar anak muda ke dunia filsafat dengan santai sambil juga belajar cara hidup yang menenangkan internal diri. Selamat buat om Piring atas puluhan kali cetaknya. Aku sih yes.
Setelah menyelesaikan si buku hanya dalam 4 hari,
Hani Rosidaini
PS: Untuk yang tertarik bergabung klub Stoic Indonesia di Facebook, bisa cek link ini